Papantunan. Itu adalah kelompok jenis lagu yang terdapat pada seni kawih cianjuran, di samping Jejemplangan, Dedegungan, Rarancagan, Kakawen, dan Panambih. Istilah Papantunan sendiri muncul sekitar perempat pertama abad XX, di Cianjur; disematkan pada lagu-lagu gubahan RAA Kusumaningrat, atau yang lebih dikenal Dalem Pancaniti, yakni Bupati Cianjur periode 1834-1862 M.
Dalam menggubah lagu-lagu Papantunan, sang dalem terinspirasi dari kawih pantun, yakni nyanyian yang terdapat pada pertunjukan seni pantun. Adapun pantun yang dipilih sebagai sumber inspirasinya adalah kisah Mundinglaya di Kusumah. Sang dalem memang tidak mengambil kisah secara keseluruhan, melainkan mencuplik adegan Mundinglaya terbang ke Jabaning Langit, hingga kembali ke bumi setelah berhasil mendapatkan Lalayang Salakadomas. Dalam hal ini, yakinlah, sang dalem tentu menemukan nilai dan filosofi yang begitu luhur dalam penggalan adegan tersebut; bahwa di sana ada pesan untuk meraih yang diangankan harus melampaui perjuangan dan pengorbanan.
Penggubahan lagu Papantunan merupakan hasil stilasi dari kawih pantun dengan cara memperhalus, memperindah, mempercantik, serta mempertimbangkan nilai orisinalitas dan mengupayakan inovasi yang berlaku. Maka, dari penggalan kisah tadi terciptalah lagu Pangapungan, Mupu Kembang, Putri Ninun, Layar Putri, Rajamantri, Kaléon, Tatalegongan, Balagenyat, Manyeuseup, Randegan Kendor, Randegan Gancang, Mangu-mangu, serta Nataan Gunung. Tidak banyak memang. Namun lagu-lagu tersebut, saat itu (paruh kedua abad XIX) menjadi lagu-lagu populer dan kalangenan di lingkungan Kadaleman Cianjur. Dan kawih Papantunan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya seni kawih cianjuran.
Dalam perkembangannya, pola lagu Papantunan menjadi inspirasi para bujangga di kemudian hari. Maka di sekitar rentang tahun 1900-1925, muncul gubahan lagu baru dengan berpola pada lagu Papantunan; lantunan, teknik vokal, serta motif-motif melodi. Lagu-lagu gubahan baru tersebut kemudian menjelma lagu Rarancagan. Kalau saja lagu Papantunan terinspirasi dari Kawih Pantun di mana liriknya menggunakan puisi pantun, maka Rarancagan terinspirasi dari tembang Rancag dalam seni mamaca (membaca wawacan). Adapun liriknya menggunakan puisi dangding. Karena penggunaan lirik dengan puisi dangding inilah, maka terhadap Rarancagan disematkan istilah tembang. Orang Cianjur menyebutnya dengan istilah mamaos.
Beriringan dengan kemunculan lagu-lagu tembang Rarancagan, muncul pula gubahan lagu baru yang menjelma lagu Dedegungan. Lagu gubahan baru ini terinspirasi dari motif-motif melodi seni degung (klasik-instrumentalia). Kelompok lagu Dedegungan ini pun menggunakan lirik puisi dangding. Seperti terhadap lagu-lagu Rarancagan, maka terhadap lagu-lagu Dedegungan pun harus disematkan istilah tembang. Maka, dalam kawih cianjuran dikenallah kelompok lagu tembang, yakni Rarancagan dan Dedegungan, di mana lirik dari kedua kelompok lagu ini menggunakan puisi dangding.
Dan akhirnya, sekitar tahun 1930-an muncul lagi kreasi lagu baru, yakni lagu Kakawén. Itu adalah lagu yang terinspirasi dari kawih kakawian dalam seni padalangan. Liriknya tidak menggunakan puisi dangding, melainkan puisi kakawian. Karenanya, terhadap kelompok lagu kakawen tidak disematkan istilah tembang. Pada tahun ini pulalah mulai populer lagu-lagu panambih.
Lagu-lagu Papantunan, Jejemplangan, Rarancagan, Dedegungan, dan Kakawen memiliki pola irama merdeka. Dalam performa seni cianjuran kelompok lagu-lagu ini disebut sebagai lagu poko, yakni lagu utama yang kedudukannya lebih ‘penting’ dan lebih ‘tinggi’ dari lagu Panambih (penambah, pelengkap). Karena predikat utama itulah, maka posisi lagu poko harus dilantunkan lebih dulu dari lagu panambih.
**
Pemikir kawih cianjuran, Ubun R. Kubarsah, menyebutkan penciptaan lagu Papantunan oleh RAA Kusumaningrat, lebih mirip pada cara kerja Ludwig van Beethoven dalam mengkomposisikan lagu-lagunya yang terinspirasi dari epos Yunani atau dari puisi-puisi panjang. Adegan demi adegan dari kisah panjang itu ditafsir ke dalam bahasa musik yang begitu indah. Pun demikian RAA Kusumaningrat, adegan Mundinglaya terbang ke Jabaning Langit lalu ditafsirnya ke dalam sebuah komposisi lagu, dan menjelmalah lagu Pangapungan. Atau di saat Nyi Dewi Asri tengah menunggu Raden Mundinglaya yang sedang terbang, ditafsirnya ke dalam lagu Mupu Kembang; Nyi Rajamantri marah ditafsirnya menjadi lagu Rajamantri; atau suasana telaga dan taman asri beserta kumbang yang menghirup bunga ditafsirnya ke dalam lagu Balagenyat, Manyeuseup, Putri Ninun, dan Layar Putri. Lagu-lagu gubahan tersebut berangkai-bersinambung. Indah dan menawan.
Sayangnya, rangkaian lagu-lagu Papantunan yang berkesinambungan tersebut dalam perkembangannya seperti sengaja dicerai-beraikan. Dimutilasi. Satu persatu lagu Papantunan dipaksa’ dipisahkan dari rangkaiannya. Kemudian disandingkan dengan lagu yang sama sekali berbeda silsilah dan latar belakangnya; umpanya lagu Manyeuseup dari Papantunan, disandingkan dengan lagu Jemplang Leumpang dari kelompok Jejemplangan, dan bahkan dengan lagu Kinanti Degung dari kelompok Dedegungan. Maka terjadilah satu performa lagu Manyeuseup, Jemplang Leumpang, Kinanti Degung, serta diteruskan dengan lagu Panambih Toropongan umpamanya. Lihatlah, kedudukan lagu Manyeuseup dalam rangkaian tersebut sejatinya sudah termutilasi dan tercerabut dari ‘keluarganya’, lalu dengan sengaja ‘disandingkan’ dengan lagu dari habitat lain.
Peristiwa pemutilasian ini lebih jelas lagi terjadi di saat dunia industri rekaman mengharu-biru. Para seniman yang suaranya akan direkam terpaksa menyusun lagu secara manasuka. Alhasil, kebutuhan industri yang memegang teguh efektif dan efisien menjadi panglima. Formula baru pun muncul, bahwa satu performa kawih cianjuran akan terdiri atas dua sampai empat lagu poko, dan satu lagu panambih.
Jika pada suatu saat dijumpai rangkaian performa Manyeuseup, Liwung, Bayubud, serta panambih Lokatmala, makan jangan heran di saat lain akan dijumpai Kaléon, Jemplang Pamirig, Kéntar Ajun, serta panambih Lembur Singkur. Lagu Kaléon, atau lagu papantunan lainnya seperti begitu saja dicerabut secara enteng, dan ditempatkan pada lokus lain secara enteng pula. Dalam posisi seperti itu, lagu Kaleon sesungguhnya telah terenggut dari habitatnya. Pemutilasian itu masih berlangsung hingga saat ini tanpa ada yang harus terusik, atau menggugat dan mungkin menghakiminya. Semuanya berjalan begitu saja, seolah tidak ada sesuatu yang aneh dan tidak wajar.
Dulu, hingga awal abad XX, etika melantunkan lagu Papantunan karya Dalem Pancaniti itu demikian tertib. Terangkai dari lagu awal Pangapungan sebagai tafsir adegan Mundinglaya terbang ke Jabaning Langit, hingga lagu penutup Nataan Gunung sebagai tafsir adegan Mundinglaya membawa Nyi Dewi Asri terbang ke langit sembari menerangkan ihwal gunung-gunung yang menghampar di bawahnya.
Maka alangkah eloknya, jika satu performa kawih cianjuran berisikan lagu poko dari kumpulan lagu kelompok tertentu. Tidak disamakbrukkan (istilah Enip Sukanda) satu kelompok lagu yang satu dengan kelompok lagu lainnya. Dengan begitu ketertiban dan etika sajian akan terasa lebih santun. Dan tentu saja asri. Pun. 



















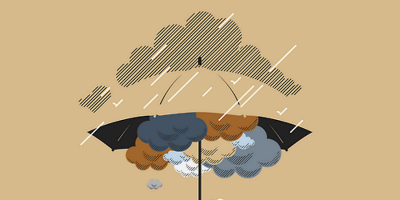
KOMENTAR ANDA