 Sekitar tahun 30-an materi seni budaya Jawa Barat diajukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, serta instansi terkait lainnya, ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, untuk dijadikan Materi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).
Sekitar tahun 30-an materi seni budaya Jawa Barat diajukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, serta instansi terkait lainnya, ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, untuk dijadikan Materi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).
Namun hanya tiga materi saja yang diakui. Ketiga materi budaya tersebut adalah Sintren (Kabupaten Cirebon), Upacara Ngarot (Kabupaten Indramayu), dan Mamaos (Kabupaten Cianjur).
Seperti dilaporkan Kadisparbud Provinsi Jawa Barat, Drs. Nunung Sobari, hingga saat ini sudah ada 13 materi seni budaya dari Jawa Barat yang sudah diakui oleh pihak Kementrian Pendidikan dan Kabudayaan, termasuk di dalamnya kujang, tari Ronggeng Gunung, Gotong Singa, dan lain-lain. Kecuali terhadap materi ‘mamaos’, materi-materi lainnya tak memiliki potensi disinterpretasi. Dan karena itu, dalam tulisan ini saya ingin menyorotinya, sekadar upaya awal penelusuran epistemologi dari istilah mamaos itu sendiri.
Istilah ‘mamaos’ berasal dari kata ‘mamaca’. Istilah ‘mamaca’ itu sendiri memiliki makna ‘membaca’. Adapun kegiatan ‘membaca’ dalam terminologi ini adalah membaca naskah wawacan atau (bisa juga) teks guguritan. Kegiatan mamaca ini, dalam kesusastraan Sunda, populer di abad XIX, ketika teks wawacan dibaca dan lalu ditembangkan.
Maka, ada tiga variabel yang sangat berkaitan satu sama lainnya, yakni mamaca (mamaos), teks wawacan (atau bisa juga guguritan), dan menembang. Mamaca adalah kegiatan membaca wawacan; wawacan itu sendiri adalah teks puisi (cerita) yang ditulis menggunakan aturan pupuh; serta kegiatan melantunkan lagu berdasarkan teks berbentuk pupuh yang sangat kita kenal dengan istilan tembang.
Hampir di seluruh Jawa Barat, kegiatan membaca wawacan kerap dilakukan dengan cara dilantunkan. Lantunan lagu dengan berdasarkan puisi berbentuk pupuh ini biasa menggunakan langgam lagu rancag, yakni lagu berirama bebas (atau tak terikat dengan aturan metrum, simetris, serta wiletan). Bagi pelantun yang berkemampuan lebih, langgam rancag ini kerap dilantunkan dengan menggunakan improvisasi yang bersumber dari lantunan kawih beluk. Karenanya, di beberapa daerah di Jawa Barat, kegiatan membaca (atau menmbang) wawacan kerap disebut dengan ‘beluk’. Padahal yang terjadi adalah, membaca atau menembang wawacan dengan gaya beluk.
Jauh setelah Kangjeng Dalem Pancaniti (RAA Kusumaningrat, Bupati Cianjur 1832-1864) meramu kawih pantun (yang biasa dilantunkan sang juru pantun) menjadi sebuah kreasi baru (yang di kemudian hari dikenal sebagai papantunan), para seniman kadaleman pada era RAA Prawiradiredja II (Bupati Cianjur 1864-1910) mencoba meramu tembang rancag menjadi lagu kreasi baru pula, yang di kemudian hari dikenal sebagai lagu-lagu Rarancagan.
Bahkan setelah muncul ramuan baru dari tembang rancag, masih di era RAA Prawiradiredja dan kemudian pada era RA Wiranatakusumah V (Bupati Cianjur 1912-1920), muncul lagi ramuan baru yang diambil dari sari-sari melodi lagu (instrumentalia) degung. Ramuan baru tersebut di kemudian hari dikenal sebagi lagu-lagu Dedegungan.
Nah, baik lagu-lagu Rarancagan maupun Dedegungan, keduanya menggunakan lirik yang berasal dari puisi dangding (puisi berbentuk pupuh, bisa wawacan bisa pula guguritan). Dan terhadap kedua jenis lagu (kreasi baru) inilah, masyarakat Cianjur menyebutnya dengan istilah ‘mamaos’ (sebagai bentuk halus dari kata ‘mamaca’, yang boleh jadi secara musikal lagu-lagu kreasi baru yang disebut sebagai ‘mamaos’ ini memiliki melodi serta karakter yang lebih halus dari ‘mamaca’ atau tembang Rancag tadi).
Jadi, yang disebut dengan istilah ‘mamaos’ lebih merujuk pada lagu-lagu Rarancagan dan Dedegungan dalam seni Cianjuran. Sementara yang disebut Cianjuran (secara teoritis serta historis) meliputi lagu-lagu yang berjenis Papantunan (juga Jejemplangan), Dedegungan, Rarancagan, Kakawen, serta Panambih. Dan jika istilah ‘mamaos’ dalam nomenklatur warisan budaya tak benda (WBTB) merujuk atau identik dengan Cianjuran, maka nomenklatur tersebut adalah keliru. Mamaos hanya merujuk pada Rarancagan dan Dedegungan, sedangkan Cianjuran lebih luas dari itu, yakni meliputi juga lagu-lagu Papantunan, Jejemplangan, Kakawen, dan Panambih.
Kerancuan Istilah
Masyarakat memang kerap dirancukan dengan istilah mamaos, tembang, tembang Sunda, tembang Sunda Cianjuran, dan Cianjuran. Kelima istilah tersebut dipandang sebagai istilah-istilah yang memiliki arti sama, yakni seni Cianjuran. Padahal kelima istilah tersebut memiliki arti dan silsilahnya masing-masing.
Istilah ‘tembang’ dalam kamus bahasa Sunda didefinisikan sebagai lagu yang bersumber pada teks pupuh. Artinya, siapapun itu yang melantunkan teks berbentuk pupuh, maka seseorang itu serta-merta disebut tengah menembang. Istilah ‘tembang Sunda’ merujuk pada tembang yang ada di masyarakat Sunda.
Dalam etnografi atau etnologi, label ‘Sunda’ yang disematkan di belakang variabel tembang, mesti dibaca sebagai pembeda dari ‘tembang Jawa’ dan ‘tembang Bali’. Sebagaimana kita ketahui, di masyarakat Bali dan terutama Jawa, dikenal pula entitas sastra (lagu, sekar) yang bernama pupuh.
Adapun istilah ‘tembang sunda Cianjuran’ merujuk pada lagu-lagu ‘tembang Sunda’ yang berada dalam seni Cianjuran. Dan lagu-lagu inilah yang akan merujuk pada materi Rarancagan dan Dedegungan, karena kedua jenis materi lagu tersebut sama-sama menggunakan teks berbentuk pupuh.
Selain ‘tembang Sunda Cianjuran’ masyarakat Sunda mengenal pula ‘tembang Sunda Ciawian’ dari daerah Ciawi Tasikmalaya dan ‘tembang Sunda Ciagawiran’ dari daerah Limbangan Garut. Kedua tembang Sunda ini –seperti juga Rarancagan dan Dedegungan dalam Cianjuran, sama-sama menggunakan teks berbentuk pupuh.
Sekali lagi, istilah mamaos yang dipergunakan oleh masyarakat Cianjur hanya merujuk pada lagu-lagu Cianjuran yang menggunakan lirik dangding (pupuh). Itu adalah lagu Rarancagan dan Dedegungan. Terhadap lagu-lagu Papantunan, masyarakat Cianjur kerap menyebutnya sebagai lagu Pajajaran atau lagu Pantun, bukan tembang Sunda ataupun mamaos. Ini bisa dimengerti, karena lagu-lagu Papantunan adalah lagu yang dikreasi dari cerita pantun (Mundinglaya di Kusumah), yang bercerita seputar konflik di seputar istana kerajaan Pajajaran, di mana teksnya berupa puisi pantun; bukan puisi dangding (pupuh).
Juga terhadap lagu-lagu Jejemplangan, masyarakat Cianjur kerap menyebut sebagai Pantun Barang. Istilah ini memiliki makna sebagai bagian dari lagu Papantunan, hanya saja nada-nadanya lebih banyak bertumpu pada nada barang (1, da); adapun nada pada lagu-lagu Papantunan lebih banyak bertumpu pada nada mi (2) dan la (5). Baik lagu-lagu Papantunan maupun lagu-lagu Jejemplangan sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan tembang atau mamaos atau materi pupuh.
Kembali ke istilah Cianjuran. Hingga saat ini yang dimaksud dengan cianjuran adalah sebuah seni yang merujuk pada pertunjukan seni vokal Sunda yang diiringi dengan kacapi indung, kacapi rincik, suling, dan rebab --untuk keilaharan laras salendro.
Untuk melantunkan lagu-lagu dalam cianjuran biasa terdiri atas dua juru sekar (juru kawih, penyanyi), boleh pria dengan wanita, boleh wanita-dengan wanita, atau hanya seorang wanita saja. Dan jika yang dimaksud dengan istilah ‘mamaos’ dalam materi WBTB tadi merujuk pada seni cianjuran, maka istilah ‘mamaos’ yang dimaksud bisa dikata keliru. Karena mamaos sejatinya hanya merupakan bagian saja dari seni cianjuran. Karenanya, istilah ‘mamaos’ yang diuruskan dalam WBTB tadi sebaiknya diganti dengan istilah ‘Cianjuran’. 




















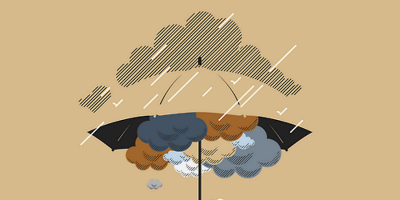
KOMENTAR ANDA