 Aku menatapnya dalam-dalam. Menatap tubuh yang sedang terkulai lemah itu. Aku memperhatikannya dengan saksama tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku takut akan menggoreskan luka yang mendalam lagi pada lubuk hatinya jika aku salah bicara.
Aku menatapnya dalam-dalam. Menatap tubuh yang sedang terkulai lemah itu. Aku memperhatikannya dengan saksama tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku takut akan menggoreskan luka yang mendalam lagi pada lubuk hatinya jika aku salah bicara.
Matanya yang sayu hanya menerawang ke langit-langit dengan tatapan kosong. Dia sesekali tersenyum. Tapi, aku tahu bahwa senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Membuatku yakin bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Aku tahu bahwa ia merasakan kehadiranku di sini. Ingin sekali rasanya aku menghampirinya. Merengkuh tubuhnya. Meneduhkan hatinya.
Tapi, aku sama sekali tidak berani barang sekali pun untuk melangkah mendekatinya. Kucoba untuk memanggil namanya. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Ah, tak ada jawaban. Ia sama sekali bergeming walaupun aku tahu bahwa ia mendengar jelas panggilanku itu.
Siluet tubuhnya kelihatan samar-samar. Kini, ia sedang duduk di tepi ranjangnya. Pandangannya lurus ke arahku. Kilatan cahaya matanya menatapku tajam. Sayangnya, itu hanya tatapan kosong. Hampa. Tak berarti apa-apa. Aku merasakan bahwa ia sangat terluka. Tatapan hampa itu mengisyaratkan bahwa ia sedang dalam masalah. Iya, memang benar. Saat ini, ia sedang dirundung kedukaan.
Sebuah kenyataan membuatnya sangat rapuh. Sang model superstar itu kini hanya tertunduk lesu meratapi nasibnya. Ia seperti kehilangan harapan untuk kembali kepada kenyataan. Kembali menjalani kehidupan yang harus ia hadapi. Dulu, dengan gesitnya ia berlenggak-lenggok berjalan di tengah panggung. Memamerkan keindahan tubuhnya. Melempar senyum pada siapa saja yang melihatnya.
Kini, berjalan di atas roda kehidupan pun rasanya ia sudah tak sanggup. Aku menyesal tidak dapat berbuat apa-apa padanya saat keadaannya sedang seperti ini. Oh, Shiera. Kau ini sahabatnya. Mengapa kau tak bisa melawan ketakutanmu itu untuk mencoba menghampirinya? Aku menggerutu pada diriku sendiri. Seharusnya aku minimal bisa dijadikan tempat untuk berbagi cerita. Seharusnya aku tak boleh membiarkannya memikul beban itu sendirian.
Tapi nyatanya, saat ini aku hanya berdiri kaku sambil menggenggam gagang pintu. Idiot sekali. Oh, Shiera. ke mana lelucon-lelucon klasik yang biasanya kau berikan untuk membuatnya selalu tersenyum? Ke mana sisi di dalam dirimu yang selalu membuatnya merasa nyaman saat berada di dekatmu? Mengapa rasanya saat ini kau merasa asing dengannya? Shiera yang bodoh. Aku menyesal pada diriku sendiri atas sikap acuh tak acuh ku saat ini padanya.
Aku menatapnya lagi ketika bulir-bulir air mata itu jatuh di tangannya. Oh, Shiera. Mengapa sekarang kau membiarkannya menangis seperti itu? Ke mana kedua tanganmu yang selalu menadahi air matanya agar tak pernah sampai jatuh ke bumi? Ironis. Mengapa saat ia membutuhkanku, aku malah tak ada untuknya. Aku tersentak ketika ia mulai bangkit dari ranjangnya.
Ia melangkah gontai ke arahku. Tubuhnya terlihat saat ringkih. Rapuh. Mudah sekali terjatuh. Ia menatapku lirih. Seakan-akan ia ingin menumpahkan seluruh beban kepenatannya itu padaku. Belum sempat ia meraih tanganku, langsung kupeluk tubuhnya erat-erat. Ku tempatkan posisi ku senyaman mungkin sebagai sandaran untuknya mengadu.
Mungkin kebanyakan orang akan berpikir untuk meninggalkannya di saat keadaan seperti ini. Tapi, itu tak berlaku untukku. Bahkan saat ini, aku ingin sekali selalu berada di dekatnya. Memikirkan untuk meninggalkannya saja pun tidak. Apalagi untuk benar-benar meninggalkannya. Tak sampai hati jika aku melakukannya.
Ku belai rambutnya dengan lembut. Berharap bisa sedikit membuatnya lebih tenang. Ku tuntun ia supaya kembali ke ranjangnya. Ku genggam tangannya erat-erat. Tangan yang begitu dingin dan gemetar. Genggaman tangannya semakin lama semakin kuat. Mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin ditinggalkan olehku. Iya, Disha. Kau tenang saja. Aku takkan mungkin meninggalkanmu. Sayang, aku tak sanggup mengatakan kata-kata itu padanya.
Ah, Shiera! Tolong untuk kali ini kau harus bisa diajak berkompromi. Jangan menumpahkan air mata seenaknya saat sedang seperti ini. Jangan menambah kedukaannya. Fokus. Buat ia jauh lebih nyaman. Bukan malah membuatnya tambah bersedih. Kepalanya kini bersandar dibahuku.
Aku memperhatikan setiap detail tubuhnya. Rambut yang dulu terurai berkilauan, kini menggumpal kusut tak karuan. Bibir merah merona yang dulu selalu menyunggingkan senyum menawan, kini membiru dan tampak pucat. Ia benar-benar berbeda. Dalam tempo waktu 24 jam, seluruh keceriaan, keriangan, kebahagiaan yang dulu selalu menghiasi hidupnya, mendadak sirna.
Ayo Shiera, kembalikan Disha seperti dulu. Kalau saja bisa, akan kulakukan apapun untuk Disha agar ia kembali lagi seperti sedia kala. Kami masih tenggelam dalam diam. Berharap ia mulai berbicara. Ayo, Disha. Aku siap mendengarkan semua keluh kesahmu itu.
“Ra,” ujarnya lirih. Akhirnya ia mulai berbicara walaupun hanya memanggil namaku saja. Yang penting ia mulai membuka dirinya.
“Sepertinya, tak bernyawa akan jauh membuatku lebih baik” Oh, Disha. Mengapa kalimat putus asa itu bisa terlontar dari mulutmu. Aku tak tau harus menanggapi apa atas kalimat yang diucapkannya tadi.
“Ra, Mengapa hidup itu cuma bisa indah sewaktu-waktu saja? Mengapa tak bisa selamanya hidup itu indah? Itu membuatku takut untuk menikmati hidup. Takut kalau sewaktu-waktu keindahan itu sirna dan berganti menjadi kedukaan," katanya memberikan pertanyaan klasik tapi sulit untuk dijawab.
“Sudahlah, Sha. Hapus pikiran-pikiran negatif itu. Fokus pada hidupmu. Jangan berpikir yang tidak-tidak,” hanya itu yang bisa ku ucapkan padanya. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi.
“Hidup bisa terlihat indah tergantung dengan persepsi kita. Kalau yang kau pikirkan selalu tentang kenestapaan seperti itu, yang kau dapatkan bukanlah keindahan, kebahagiaan, ataupun kenikmatan hidup melainkan kedukaan yang datang silih berganti. Mungkin kau jatuh hari ini. Jatuh dalam kesedihan. Kesengsaraan. Terluka. Tapi, aku yakin keindahan hidup akan datang dan mengobati luka yang kau alami itu. Cepat atau lambat," kataku.
“Shiera, aku terjatuh pada lubang kedukaan yang terlalu dalam. Mana mungkin aku bisa bangkit pada luka sedalam ini? Aku ingin menyerah saja, Ra. Ini baru dua puluh empat jam. Tapi, rasanya sudah berabad-abad penderitaannya,” Ia mulai menitikkan air matanya lagi.
Aku belum berhasil membuatnya kembali. Aku tak tahu lagi apa yang harus ku perbuat. Membuatnya jauh lebih tenang saja rasanya sulit sekali. Apalagi membuatnya tersenyum bahagia. Aku benar-benar tak sanggup.
“Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Kau menginginkan kebahagiaan sekarang, tapi Tuhan justru memberikanmu kedukaan. Itu berarti Tuhan tahu kebutuhanmu. Kau butuh untuk disadarkan. Tuhan ingin kau membuka matamu untuk bisa memahami dan menerima kenyataan bahwa tak selamanya manusia menikmati keindahan pada hidupnya,” aku menghela napas sejenak.
Menunggu balasan darinya. Aku takut ia tersinggung dengan perkataanku. Alih-alih membuatnya tenang, aku justru membuatnya semakin emosi saja.
“Tapi, mengapa harus sekarang? Mengapa ini terjadi di saat aku sedang di puncak kebahagiaan? Jatuhnya jauh lebih menyakitkan kalau seperti ini keadaannya, Ra. Lukanya menjadi semakin sulit untuk diobati. Kau tidak tahu betapa malangnya nasibku ini. Kau tidak bisa merasakan apa yang ku rasakan saat ini. Aku kehilangnya semuanya. Orang tua, keluarga, harta, karier, reputasi, dan masa depan. Lantas, untuk apa aku hidup?” ujarnya lirih.
Disha memang benar. Aku tak bisa merasakan apa yang ia rasakan. Aku tak tahu betapa hancurnya hati Disha saat ini. Betapa kuat tekadnya untuk mengakhiri saja hidupnya yang menurutnya sama sekali tak berguna.
“Aku sudah merasakan segala macam rasa sakit, sakitnya dikhianati, icampakkan, dibuang, tidak dipedulikan, dan dianggap tidak ada. Harga diri pun rasanya aku sudah tak punya. Apa kau pernah merasakan pahitnya hidup seperti itu, Ra?” SKAKMAT. Aku benar-benar membisu saat ini. Lidahku kelu. Hatiku bergetar hebat.
“Aku membangun semuanya dari nol bertahun-tahun lamanya. Menitinya dengan sepenuh hati. Persis sama dengan orang-orang yang meniti jembatan gantung, perlahan, hati-hati, cermat. cekatan, dan enjaganya dengan penuh pengorbanan. Setelah semuanya kudapatkan dengan bersusah payah, tiba-tiba lenyap begitu saja dalam kurun waktu dua puluh empat jam. Siapa yang tidak berduka, Ra? Siapa yang tidak hancur? Siapa yang tidak meratap? Saat ini, aku tak punya apa-apa. Tak punya siapa-siapa.”
“Ada aku di sini, Sha. Kau masih memiliki kesempatan menata hidupmu kembali bersamaku. Barangkali luka hatimu itu sedikit banyak akan terobati jikalau aku diizinkan menemani dan membantumu. Biarlah badai dengan dahsyatnya merusak kebahagiaanmu saat ini. Tapi, tetaplah berharap bahwa akan ada cahaya mentari yang menerangi hidupmu sepanjang hari. Menghalau badai yang selalu mengusik kehidupanmu itu,” tiba-tiba saja tanpa menghiraukan perkataanku, Disha pergi secepat kilat.
Ia meninggalkanku yang masih terpaku dalam kebingungan. Keadaan Disha saat ini memang tak bisa diketahui secara gamblang. Aku sama sekali tak mengenalinya. Aku tak bisa menerka-nerka bagaimana keadaan dirinya. Tak bisa menembus kedalam hatinya untuk mengetahui apa yang ia rasa saat ini. Tapi yang jelas, aku sangat menyayangi Disha. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menemaninya. Saat ia membutuhkanku ataupun tidak, aku bersedia selalu ada di sampingnya.
Kicauan burung yang selalu menghiasi hari-harinya, mungkin takkan pernah ia hiraukan lagi. Rerumputan hijau yang selalu menyapanya di pagi hari, mungkin takkan pernah ia pedulikan lagi. Aroma bunga-bunga yang mewangi setiap mentari ada di ufuk barat pun, mungkin takkan pernah ia rasakan lagi. Kesunyian malam yang menenangkan pun justru membuat hidupnya semakin mencekam dalam kesendirian. Tapi, meskipun keadaannya terlihat mengenaskan seperti itu, aku akan tetap pada pendirianku. Mana mungkin aku tega meninggalkannya dalam duka nestapa seperti itu?
“SHIERAAA,” suara teriakan itu membuatku terlonjak kaget. Disha. Ya, itu suara Disha! Ya, Tuhan. Ada apa lagi dengan dirinya?
“Ada ap...”perkataanku terhenti ketika aku melihatnya sedang berdiri menggenggam sebuah buku. Bukan. Bukan sebuah buku. Melainkan... sebuah album foto, sepertinya.
Kami membuka album foto usang itu secara perlahan. Mengamati setiap lembar foto yang terletak pada album foto tersebut. Bukan. Isinya bukan foto. Melainkan... Tunggu dulu, SURAT? Apa aku tidak salah lihat? Tidak, aku memang tidak salah lihat. Ada puluhan surat yang tersusun rapi pada album foto tersebut. Surat yang sudah menguning. Tanda bahwa surat tersebut sudah dibuat bertahun-tahun lalu. Isinya cukup mencengangkan.
Dear, Disha
Nak, ini aku. Aku ini, ibumu. Ya, benar. Aku ini memang ibumu. Ibu yang mungkin tak pantas kau panggil dengan sebutan “ibu”. Ibu yang terlalu hina. Terlalu egois. Terlalu tabu untuk dianggap sebagai seorang ibu. Nak, mungkin saat kau membaca surat ini, Ibu sudah tak bersamamu lagi. Oh, iya. Ibu lupa. Kita memang sudah tak bersama sejak sepuluh tahun silam, bukan? Sudahlah. Tak ada gunanya membahas sesuatu yang telah berlalu.
Nak, ibumu ini terlalu malu untuk menampakkan diri padamu. Ibu memang lah seorang pengecut. Ayahmu saja rasanya sudah tak sanggup untuk hidup lebih lama lagi dengan ibu. Oleh karena itu, ia putuskan untuk meninggalkan ibu. Oh, tidak. Ibu lupa. Ibu yang meninggalkan ayahmu, dan tentu saja... Meninggalkanmu juga. Ibu menyesalinya, Nak. Menyesali perbuatan yang sudah ibu lakukan sepuluh tahun silam itu. Ibu tak tahu bagaimana caranya menebus dosa yang telah ibu lakukan padamu dan tentunya... pada ayahmu juga. Ribuan maaf, ribuan penyesalan, bahkan ribuan pengorbanan pun takkan pernah berarti dibandingkan rasa penderitaan yang kau dan ayahmu rasakan.
Disha, anakku... dimulai dari surat yang pertama ini dan akan berlanjut pada surat-surat berikutnya, ibu akan membeberkan kepadamu apa yang ibu rasakan saat ini dan tahun-tahun yang akan datang. Ibu kesepian, Nak. Ibu memendam penyesalan. Kesedihan, kerinduan. Sejak meninggalkanmu itu, Ibu selalu dirundung kedukaan. Untuk menebar senyum saja rasanya Ibu tak bisa, Sha. Kalau pun ada secercah harapan untuk berbahagia, mungkin hanya sepersekian detik saja bisa ibu rasakan. Ingin rasanya ibu menemuimu. Memelukmu hangat. Memberikan cinta dan kasih yang selama ini tak pernah ibu berikan padamu.
Disha, jaga dirimu baik-baik. Jangan menjadi wanita tak berharga diri. Jangan menjadi wanita yang miskin hatinya. Jangan menjadi wanita yang mudah tergoyahkan oleh kenikmatan dunia, Nak. Jangan menjadi wanita seperti ibu. Hina,kotor, bermandikan kesalahan. Berlumuran dosa.
Jaga ayahmu juga, ya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai ia jatuh pada wanita seperti ibu lagi. Ayahmu itu bagai emas yang jatuh di dalam lumpur. Berkilauan saat jatuh pada wanita kotor seperti Ibu. Menyesal lah ayahmu pasti saat ia pernah memiliki ikatan kasih dengan wanita laknat seperti ibumu ini. Ibu selalu berharap yang terbaik untukmu, Nak. Jangan bernasib sama seperti ibu. Terlena oleh kenikmatan dunia. Sehingga kehilangan segalanya. Harta, orang tua, keluarga, reputasi, masa depan, bahkan orang yang paling disayang yang notabene adalah AYAHMU.
Sekian surat perdana dari ibumu ini. Selamat menikmati goresan tangan tak berdaya ini pada lembar-lembar berikutnya. Ibu berharap kau bisa membacanya entah kapan dan bagaimana pun caranya. Berbahagia lah bersama ayahmu. Jangan kau tinggalkan ia seperti ibu meninggalkannya dahulu.
PERINGATAN. Ya, benar. Itu adalah sebuah peringatan. Sayangnya, peringatan yang sudah terlambat. Disha sudah kehilangan segalanya. Sama seperti apa yang dialami oleh ibunya. Itu semua juga terjadi dengan penyebab yang sama. Sama-sama karena terlena pada kehidupan di dunia. Sampai rela meninggalkan suami dan anak. Sampai tega meninggalkan ayah. Kini, aku mengerti. Aku mendapat sebuah pengalaman berharga dari kenyataan yg menurutku terlalu rumit ini. Sayang, kenyataannya tak berakhir bahagia.
“Ra, mau kah berjanji padaku untuk membantuku bangkit kembali? Mengobati luka hatiku perlahan? Menemaniku untuk mencoba menerima kenyataan? Aku telah memahami semuanya lewat surat-surat ini, Ra,”
“Shiera, kau memang sepenuhnya benar. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Aku sedang butuh untuk ditegur dan Tuhan sedang menegurku lewat ujian ini. Aku menyesali segalanya, Ra. Sayang, penyesalan itu sudah tak ada artinya. Takkan bisa mengembalikan apapun yang telah hilang dalam hidupku, terutama... Ayahku” Oh, Tuhan. Ia memelukku erat dan... Dia tersenyum kembali!!! Ini aneh.
Secepat itu kah ia kembali pada jiwanya seperti dua puluh empat jam yang lalu? Surat itu membuat hatinya terbuka sangat cepat. Ah sudahlah. Yang terpenting saat ini aku harus bisa membuatnya menikmati hidup kembali. Menemaninya supaya bisa belajar merasakan apa yang ia rasakan. Membangkitkannya ketika ia terjatuh. Mengingatkan pada apapun yang ia perbuat agar tidak menyesal dikemudian hari seperti yang ia lakukan saat ini.
Disha memang benar. Mungkin hidup itu membuat kita menjadi letih, jenuh, dan bosan. Kehidupan kadang memiliki banyak makna tersirat yang sulit dipecahkan. Setelah berhasil memecahkan dan ternyata keputusannya salah... penyesalan lah yang akan terjadi. Penyesalan membuat semuanya terkesan menyedihkan. Terkadang mungkin sampai berpikir untuk menyerah pada dunia karena telah menyesali keputusan. Berpikir bahwa tak bernyawa pun lebih baik rasanya.
Tapi, apa kita mau menyerah begitu saja pada dunia yang penuh sandiwara ini? Apakah kita ingin hanya dikenang sebagai seorang pengecut? Pencundang? Yang kalah sebelum berperang. Yang lari dari kenyataan. Lari dari kehidupan yang terus berjalan. Tentu tidak. Lari dari kenyataan takkan pernah bisa menyeselaikan masalah dalam hidup. Justru membuat kita tenggelam dan terjebak pada permasalahan lain yang bahkan akan jauh lebih sulit. 













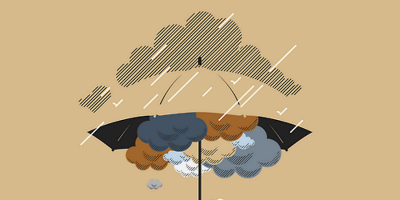








KOMENTAR ANDA