 Beberapa waktu yang lalu saat berselancar di media sosial, saya menemukan kawan saya sedang asyik berbantah-bantahan dengan seorang anonim entah siapa. Akun anonim tersebut tidak jelas namanya siapa, jenis kelaminnya apa, dan deskripsi umum tentang diri. Teman saya ini begitu kaku dan tidak ingin kalah argumennya tentang perlu atau tidaknya seorang istri memberi bekal untuk suaminya.
Beberapa waktu yang lalu saat berselancar di media sosial, saya menemukan kawan saya sedang asyik berbantah-bantahan dengan seorang anonim entah siapa. Akun anonim tersebut tidak jelas namanya siapa, jenis kelaminnya apa, dan deskripsi umum tentang diri. Teman saya ini begitu kaku dan tidak ingin kalah argumennya tentang perlu atau tidaknya seorang istri memberi bekal untuk suaminya.
Lain halnya dengan kawan saya yang mengeluh pada saya betapa ia telah sia-sia menempuh bangku pendidikan. “Cape-cape sekolah, eh dibantah sama argumen dari WhatsApp,” keluhnya tentang setelah kalah argumen mengenai ada atau tidak sebenarnya virus corona ini. Ia panjang lebar menceramahi keluarganya tentang pentingnya diam di rumah dalam upaya mencegah penularan virus, akan tetapi semua ilmu medis yang ia kemukakan dibantah oleh teori konspirasi pengguna WhatsApp.
Sementara itu, saya memiliki teman kembar yang tidak identik dan berkebalikan perangainya. Teman saya yang kembar itu, satu di antaranya begitu ambisius. Ia senang mengikuti seminar dan kajian di luar jam kuliah. Katanya, ia mengincar kesempatan pertukaran pelajar. Namun, pada saat kesempatan itu berada di tangannya, ia malah melepaskannya karena merasa tidak pantas mendapat kesempatan itu. Kembarannya lain lagi, ia tidak senang pada kembarannya yang asertif di kelas dan ambisius itu. Ia lebih memilih menjalani kehidupan kuliah yang selow.
Beberapa contoh di atas adalah fenomena perilaku yang mencancam dalam dunia pendidikan yang saya observasi menggunakan pendekatan psikologis. Karlina Supeli pada tahun 2017 pernah mengisi kuliah umum di Unpar berjudul “Ancaman Terhadap Ilmu Pengetahuan”, menjadi landasan sekaligus inspirasi saya menulis tema ini.
Merasa Tahu Banyak Hal
Kawan saya yang mendebatkan penting atau tidaknya bekal yang disiapkan seorang istri untuk suaminya menarik untuk diamati. Bukan konten perdebatannya yang menarik untuk dibahas, melainkan cara dia menyampaikan argumennya. Kawan saya begitu gigih menyampaikan argumennya, atau ngeyel dan merasa dirinya benar dengan teori yang dibawakannya.
Perilaku semacam ini dapat diteliti secara ilmiah menggunakan ilmu psikologi. Gejala psikologis ini dicetuskan oleh David Dunning dan Justin Kruger dari Cornell University, dalam penelitian ilmiah yang dilakukan sejak tahun 1999. Satu simpulan penelitian itu adalah orang dengan tingkat keahlian rendah cenderung menilai dirinya melebihi kenyataan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan membentuk khayalan bahwa dirinya hebat. Sementara itu, orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya merasa dirinya kurang baik dan perlu banyak belajar lagi.
Kecenderungan bahwa orang yang baru memiliki pengetahuan atau keterampilan pada suatu bidang merasa dirinya ahli dalam bidang tersebut disebabkan oleh hasrat keinginan untuk dipandang pintar, superior, dan tahu segala hal. Efek ini yang menyebabkan banyak munculnya orang-orang yang mendadak jadi ustaz, jadi munsyi, jadi budayawan, jadi pakar hukum, atau jadi ahli pada bidang apapun dengan bekal satu-dua kutipan dari internet. Orang dengan Efek Dunning-Kruger merasa dirinya benar dan berhak untuk menyalahkan pendapat orang lain, bahkan pada titik tertentu merendahkan orang lain karena ketidaktahuan mereka.
Perilaku seperti ini sangat tidak sehat terutama dalam dunia pendidikan. Pelajar yang memiliki efek ini cenderung reaktif dan dominan terhadap isu terbaru, tema diskusi, bahkan obrolan sederhana sekalipun. Bukankah jauh-jauh hari, Shakespeare pernah berkata, “orang bodoh merasa dirinya bijak, tetapi orang bijak merasa dirinya bodoh”.
Diskriminatif
Sikap kembaran kawan saya yang mendiskriminasi kembarannya yang asertif dan ambisius ini sering kita temui dalam keseharian. Orang yang gemar bertanya di kelas hingga menguras jam istirahat, mengingatkan ada tugas pada guru atau dosen, sampai keluar lebih awal saat ujian acap kali mendapat perlakuan diskriminatif. Orang-orang yang tidak suka ini seringmemperlakukannya berbeda, dijauhi dari komunitas sosial, terang-terangan dilecehkan di hadapan umum, hingga perundungan.
Perilaku diskriminatif semacam ini dapat membunuh perilaku asertif yang dimiliki orang lain. Orang jadi enggan bertanya atau enggan terlibat aktif pada kegiatan belajar-mengajar di kelas karena kekhawatiran mendapat perlakuan diskriminatif.
Feodalis
Dalam ranah akademik, terutama bangku perkuliah, menghormati dosen adalah hal yang diperlukan. Sikap ini adalah bentuk apresiasi kita atas jasa yang para dosen telah berikan, yakni berupa ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada beberapa budaya feodal yang semestinya tidak dilestarikan di jenjang perguruan tinggi. Salah satunya adalah sikap mencium tangan. Secara historis, sikap mencium tangan dilakukan oleh rakyat jelata terhadap kaum bangsawan kerajaan, simbol kelas antara bangsawan kerajaan dengan rakyat jelata.
Sebab itu, sikap mencium tangan yang merupakan bentuk pengakuan status inferior kita. Sikap ini melanggengkan stigma bahwa mahasiswa yang baik harus patuh pada dosen, bahwa mahasiswa tidak lebih benar dari dosen, dsb. Padahal, dosen bisa saja salah dan bisa saja bersikap keliru. Kampus sebagai tempat yang menjunjung tinggi keadilan bahkan sejak dalam berpikir ini tidak semestinya melestarikan budaya feodal semacam ini.
Merasa Tidak Layak
Kawan saya yang kembar itu dianakemasi dosen selain sebab keaktifannya di kelas, juga karena ramah dan ringan kata. Selain itu, dia penerima beasiswa dari pemerintah yang menuntutnya untuk berprestasi. Akan tetapi, ia curhat pada saya bahwa ia merasa tidak nyaman dengan kondisinya saat itu. Katanya, ia kebetulan belaka mendapat beasiswa dan kebetulan saja nilai IPK-nya besar karena hubungan yang baik dengan dosen semata. Hingga puncaknya, ia menolak kesempatan pertukaran pelajar karena merasa kemampuannya tidak sebaik yang orang pikirkan.
Gejala ini dikenal sebagai sindrom imposter. Sindrom imposter dikemukakan pertama kali oleh Pauline Clance dan Suzzanne Imes pada tahun 1970-an. Fenomena ini ditemukan pada beberapa orang ambisius yang cenderung tidak mempercayai kemampuan sendiri. Gampang cemas, tidak percaya diri atau minder, cenderung perfeksionis, dan frustasi ketika gagal memenuhi standar yang ia tetapkan sendiri merupakan gejala sindrom imposter.
Dampaknya, orang yang mengalami sindrom imposter sering tertekan dan merasa tidak layak mendapat prestasi yang akan atau telah ia peroleh. Hal ini berpotensi membunuh keinginan pelajar untuk berkembang, berprestasi, dan mengapresiasi diri.
Demikian perilaku-perilaku yang mencancam dalam dunia pendidikan. Ancaman ini perlu untuk diatasi sebab dapat membuat pelajar sulit mengembangkan diri, mengekspresikan diri, mencapai prestasi, dan mengapresiasi diri.




















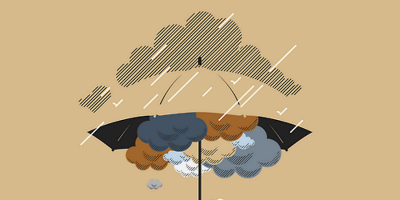
KOMENTAR ANDA