 Sebagai mahasiswa prodi Sastra Indonesia pada sebuah universitas negeri di Jatinangor, saya memiliki keinginan untuk menjadi penulis.
Sebagai mahasiswa prodi Sastra Indonesia pada sebuah universitas negeri di Jatinangor, saya memiliki keinginan untuk menjadi penulis.
Barangkali cita-cita menjadi penulis memang keinginan hampir seluruh mahasiswa sastra deh (yang enggak memiliki keinginan menjadi penulis biasanya sih mahasiswa buangan dari jurusan favorit ke jurusan sastra dan mahasiswa sastra yang bercita-cita menjadi PNS).
Siapa yang tidak mau menjadi penulis? Kerjaannya hanya duduk berlama-lama di depan laptop, cuma mikir kalimat yang tepat dan minum kopi di jendela kedai kopi sambil menikmati senja, tetapi mereka dapat duit banyak dan dikenal banyak orang bak seorang superstar, bukan begitu? Muantap betul memang menjadi seorang penulis! Top markotop! Sapardi Djoko Damono jauh-jauh hari pernah menulis pada sebuah surat kabar berjudul “Surat Kesusasteraan Buat Neng Ina” di awal tahun 2000-an, yang intinya bilang bahwa suatu hari nanti profesi penulis bakal abis dan bakal banyak penulis perempuan bermunculan.
Sekarang bisa kita lihat sendiri, toko-toko buku dibanjiri buku-buku penulis baru dan bejibun penulis perempuan bermunculan menyaingi jumlah penulis laki-laki. Keinginan menjadi penulis telah menjamur di kalangan anak muda Indonesia, sebagaimana keinginan menjadi barista, penikmat senja-senjaan, atau ustaz kondang.
“Penulis” adalah profesi yang bisa dengan bangga mereka proklamirkan suatu hari nanti di hadapan si bapak pacar sambil membawa lima kotak martabak atau dikemukakan di hadapan teman-temannya yang telah lama tidak berjumpa sambil menepuk-nepuk dadanya.
Ah, tapi apa memang iya menjadi penulis itu hal yang menyenangkan? Apa iya menjadi penulis adalah hal yang mudah? Apa iya menjadi penulis itu bisa dapet gengsi yang tinggi di mata sosial? Apa iya menjadi penulis itu bisa dipuja-puja penggemar dan dapet follower/subscriber yang banyak? Apa iya? Semula saya berpikir begitu.
Toh memang tinggal menulis, kirim ke penerbit, dapet duit, selesai. Gak perlu repot. Gak perlu cape. Tapi rupanya tidak semudah itu, Ferguso! Nah, inilah sekarang saya akan menceritakannya. Pertama, generasi milenial tidak bisa menulis sastra karena ia malas.
Ya gak usah dibahas lah ya, toh tahu-sama tahu generasi milenial itu generasi leyeh-leyeh bin generasi rebahan. Nulisnya satu paragraf, main hp-nya satu periode presiden menjabat. Jangankan nulis, tugas sekolah/kuliah aja masih kopas dari Google.
Mimpi deh kalau pengen jadi penulis, tapi gak bisa bedain makna “realitas”, “realistis”, dan “realis”. Belum lagi kalau ada revisi. Bah! Kedua, generasi milenial tidak bisa menulis sastra karena ia dibuat bingung bin gamang sama definisi sastra itu sendiri.
Pasalnya, ada yang bilang kalau sastra itu cuma sebatas karya-karya serius seperti karyanya Pramoedya, Marah Roesli, Amir Hamzah, Putu Wijaya, dkk. Sementara itu, buku-bukunya Raditya Dika, Tere Liye, Fiersa Besari, Boy Chandra, dkk.
Itu menurut mereka hanyalah merupakan karya picisan. Bila ada generasi milenial yang mengimani definisi begini, ia bakal kesulitan menulis karena ia bikin standarisasi kalau sastra itu yang modelnya kayak Pram, kayak Amir Hamzah, kayak Chairil, atau kayak si anu.
Dengan kata lain, ia kudu menulis dengan dibebani sendiri oleh definisi dan standar sastra yang ia buat sebab ada ketakutan ia menulis sesuatu yang remeh alias picisan (masa aku nulis yang model begitu?) Ketiga, generasi milenial tidak bisa menulis sastra sebab ia gak diajarin nulis dan gak mau belajar teknik menulis yang baik.
Loh kok begitu? Ya memang begitu! Orang-orang model begini sudah terlanjur percaya diri berlebih, merasa karyanya paling bagus. Padahal, ia sama sekali tidak riset dan tidak membaca.
Biasanya, ia tidak akan tahu tuh yang namanya open ending itu yang kayak gimana, hold and suspen itu diletakkan di mana baiknya, gimana bikin konflik yang menjaga ritme pembaca, gimana bikin karya yang bisa laku di pasaran, dan lain-lain. Apalagi tahu tentang hal yang lebih rumit untuk keperluan menulis, seperti teori formalisme, strukturalisme, dan post-struktualisme.
Sebagai calon penulis, ya mana ngerti nerapinnya gimana, bukan? Keempat, generasi milenial tidak bisa menulis karena gak ada wadah yang menampung mereka. Wadah maksudnya bukan ember, tapi gak ada fasilitas yang mendukung mereka untuk berkarya semacam majalah sastra, komunitas menulis, dsb.
Jarang ada komunitas sastra yang saling sharing teknik menulis, saling membaca dan mengoreksi tulisan satu sama lain. Untuk alasan yang selanjutnya sampai ke 1001 saya hutang dulu. Nah, alasan-alasan yang saya tulis di atas kayaknya bukan lagi problem personal, melainkan udah menjadi problem kolektif (syukur-syukur bisa jadi problem stuktural) yang terjadi di ekosistem sastra kita.
Kita terlalu terpaku pada keinginan menjadi “penulis”, tetapi lupa bahwa ada banyak hal yang mesti kita pelajari untuk menulis. Menulis adalah kerja tabah, yang setiap langkahnya adalah ibadah. 









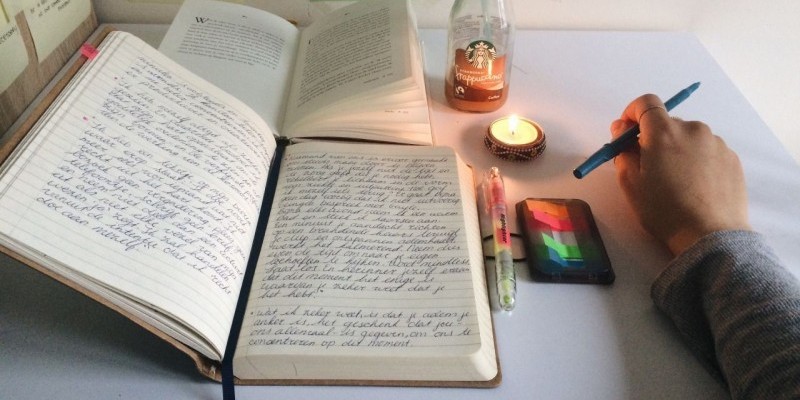










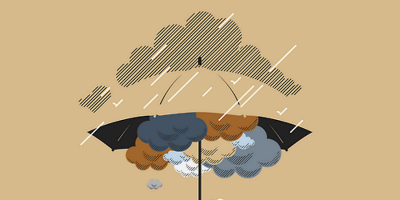
KOMENTAR ANDA